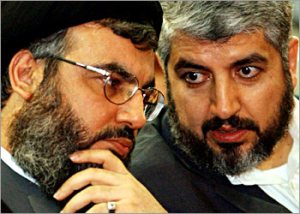
Ketika perang atas Gaza—yang ditandai dengan agresi Israel pada Sabbath, 27 Desember 2008—berlangsung, paduan suara berpengaruh di media Amerika Serikat seolah serentak menyanyikan lagu lama bahwa perang atas Gaza adalah sebuah perang proksi, dimana musuh sesungguhnya bukanlah Hamas tetapi Iran.
Hasilnya sudah bisa ditebak, tumbuhnya kecenderungan di AS untuk memandang Gaza hanya sebagai salah satu medan laga dari sebuah perang yang lebih besar antara Iran melawan Barat—atau lebih tepatnya lagi “perang global” melawan Islam radikal—dan untuk seenak perutnya mengabaikan nestapa dan penderitaan nyata bangsa Palestina di bawah pendudukan militer Israel selama enam dekade.
Cara memandang perang atas Gaza seperti ini jelas terlalu simplistik dan memiliki tendensi-tendensi dari agenda-agenda tersembunyi. Dengan melebih-lebihkan adanya bantuan Iran kepada pemerintahan terpilih Ismail Haniya, suara-suara tersebut bermaksud meningkatkan permusuhan dengan Iran, menyokong alasan absurd Israel untuk membombardir Gaza, dan menyabotase setiap kecenderungan kepada perdamaian di tanah Palestina.
Selama bertahun-tahun, sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kalangan neokonservatif Amerika untuk memotret Iran sebagai sumber ancaman paling nyata kepada kepentingan Amerika di Timur Tengah, dari Palestina hingga Lebanon, dari Afghanistan hingga Irak. Selama agresi Israel atas Lebanon pada 2006, pentolan neokonservatif William “Bill” Kristol mendesak negara-negara Barat untuk lebih memusatkan perhatian kepada “para komandan sesungguhnya” di Tehran ketimbang kepada Hamas dan Hizbullah
Dengan cara yang sama, kalangan neokonservatif berupaya menjadikan perang Israel atas Gaza ini sebagai sebuah pertanda bahwa Barat harus mengambil garis yang lebih keras terhadap Iran. “It’s all about Iran,” tulis Michael Ledeen, seorang hawkish ternama dari Foundation for the Defense of Democracies, di dalam National Review edisi 30 Desember 2008. “(Orang-orang Israel) harus rela menghadapi sungut-sungut dari dari ular naga teroris, sementara tubuh utamanya tetap tidak tersentuh. Mereka mungkin bisa memotong habis sungut Hamas atau Hizbullah, tetapi ia akan muncul lagi dan menangkap mereka.”
Dalam New York Times, pemikir neoliberal berpengaruh Thomas Friedman secara tidak langsung menyatakan bahwa Iran harus dipersalahkan atas pecahnya perang di Gaza, seraya menulis bahwa Tehran bisa “menghentikan dan memulai konflik Israel-Palestina sesuai kehendaknya.”
Dalam Los Angeles Times, analis-analis Israel Yossi Klein Halevi dan Michael B. Oren menulis sebuah opini bertajuk, “In Gaza, the Real Enemy Is Iran,” dimana keduanya memperingatkan bahwa jika Hamas “memanipulasi opini dunia untuk memaksakan sebuah gencatan senjata yang prematur…maka itu akan bermakna sebuah kemenangan lain bagi Iran.”
Kini di AS, nyaris secara luas diterima bahwa Iran sebenarnya mensuplai persenjataan dan bantuan operasional lainnya kepada Hamas dalam tahun-tahun terakhir ini. Bagaimanapun, sedikit sekali estimasi yang bisa dipercaya tentang seberapa signifikan bantuan itu bagi Hamas. “Saya sangat skeptis ketika melihat gambaran-gambaran seperti itu di media,” mantan pejabat intelijen Deplu AS Wayne White, kini analis pada Middle East Institute, mengatakan kepada Inter Press Service. “Bahkan ketika saya berada di dalam komunitas intelijen, rincian-rincian pastinya kerap tidak bisa dijadikan pegangan.
Mereka yang mempersalahkan Iran dalam kaitan dengan perang atas Gaza secara berlebihan memandang bahwa Hamas tidak lebih daripada “proksi” Iran. Namun, White berpendapat bahwa hubungan Iran dengan Hamas jauh lebih bersifat simbolik ketimbang mendikte. Baik Iran, Hamas, ataupun Hizbullah terhubungkan oleh kesamaan menghadapi tekanan imperialistik Amerika dan Israel. “Pengaruh Iran terhadap Hamas dipandang terlampau berlebihan. Hamas punya setiap alasan untuk membuat keputusannya sendiri,” kata White.
(Sumber : Buku GELAGAR GAZA)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar